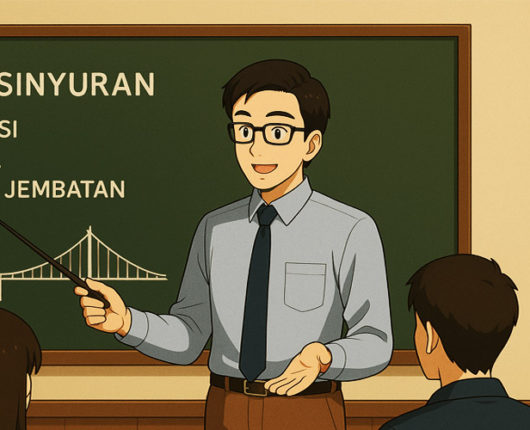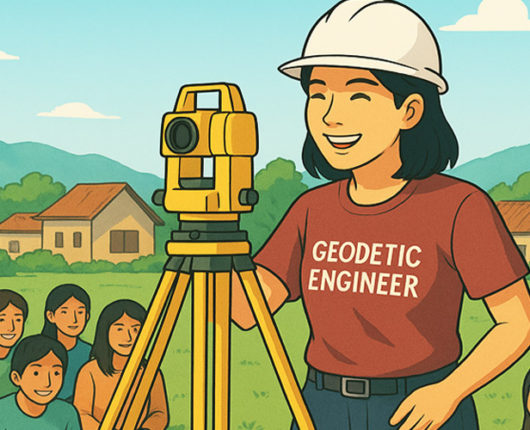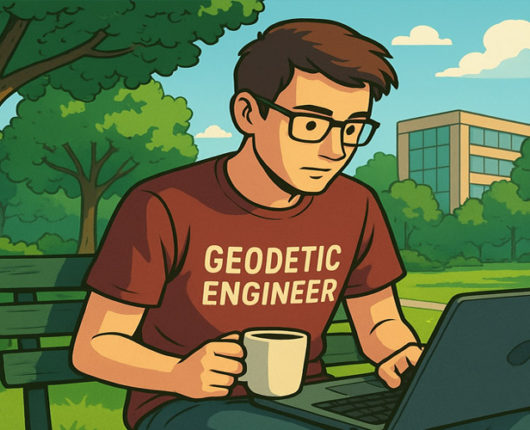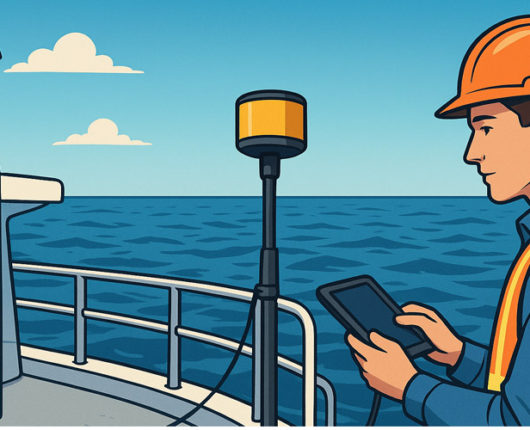Kiprah Mahasiswa Geodesi Dekade 1970an
Setiap mahasiswa yang pernah diajak ‘mroyek oleh doserinya di masa kuliah dulu mungkin tidak terlalu peduli dengan kontribusinya bagi masyarakat. Tidak heran kalau hall ini luput dari perhatian mahasiswa pada eraku, karena target utama dapat surat puas praktek ilmu ukur tanah, dan dapat uang saku. Padahal coba saja simak catatanku ini. Di awal 1973 pertama kali aku diajak ‘mroyek’ oleh seorang dosen. Aku pikir ini peluang untuk mempraktekan ilmu ukur tanah. Lokasi proyek di di Kecamatan Kencong, Jember Mengerjakan pengukuran poligon, profiling dan pemetaan situsasi sepanjang saluran irigasi Awalnya aku ditugasi menjadi asisten juru ukur mahasiswa seniorku, dan setelah satu minggu jadi asisten, aku ditugasi menjadi juru ukur hingga survei di Kencong selesai.
Dari pengalaman di atas ada empat kesan yang bisa aku catat: (1) ilmu Teknik Geodesi adalah ilmu yang berguna bagi rakyat dan manajemen air untuk lancarnya produksi padi (2) praktek lapangan memberiku pengalaman baru: hidup dan bergaul dengan alam, masyarakat dan budayanya; (3) seorang surveyor adalah seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab, profesional, jujur/terpercaya dan disiplin; dan (4) pengetahuan ilmu bumi Indonesia-ku bertambah, aku saksikan sendiri di Jawa Timur: negeriku kaya serta Indah alam dan budayanya. Itulah kesan pertama yang jadi awal dan ‘mroyek-mroyek berikutnya sebagai bekal menuju profesi surveyor.
Banyak pengalaman proyek selama mahasiswa, diantaranya: Survei Triangulasi Proyek Pertanian Pemali-Comal (Jateng, 1975), Proyek Citanduy (Jabar-Jateng, 1976) dan Pemetaan Karangkates Hulu (Jatim, 1977). “Petualangan mahasiswa mroyek ini akhimys aku sudahi setelah aku berkenalan dengan Prof. Jacub Rais di paruh kedua tahun 1977 Beliau menawarkan ikatan dinas di Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional atau BAKOSURTANAL dan langsung aku terima. Sejak Oktober 1977 aku back to campus menjadi mahasiswa Ikatan Dinas BAKOSURTANAL.
Mengenal Mancanegara Belahan Bumi Selatan
Teken kontrak ikatan dinas dengan BAKOSURTANAL untuk selama satu tahun, nyatanya aku hanya perlu waktu setengah tahun saja sebagai mahasiswa ikatan dinas. April 1978 aku diwisuda jadi Insinyur, dan langsung masuk BAKOSURTANAL, dan tepat 1 Januari 1979 aku berstatus PNS penuh. Jangan tanya berapa gajinya waktu itu. Motivasiku masuk BAKOSURTANAL adalah mewujudkan mimpiku waktu di SD “jadi Insinyur, lalu Doktor yang berdasarkan informasi dari Prof. Rais, adanya peluang terbuka melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri melalui BAKOSURTANAL. Sambil kerja, aku diberi kesempatan belajar (kursus) bahasa Inggris di Lembaga Indonesia-Amerika (LIA) dan kursus komputer di Universitas Indonesia (UI) yang lulus sangat memuaskan dalam Computer Programming.
Di penghujung tahun 1979 aku berangkat ke Sydney untuk menjalani program graduate study di UNSW (University of New South Wales). Inilah pengalaman mancanegaraku yang pertama. Hari minggu siang di penghujung Desember 1979 aku tiba di Bandara Sydney. Mungkin aku satu-satunya orang yang berpakaian lengkap yang turun dari pesawat waktu itu. Heh…maklum baru pertama ke luar negeri, harus jaga citra bangsaku. Dan aku pikir di Australia udaranya sejuk. Namun rupanya temperatur waktu itu di Sydney 42°C. Aku lihat hampir semua orang bertelanjang dada dan “klekaran” kepanasan, …sementara aku… memakai pakaian jas lengkap dengan dasinya…, inilah pengalaman pertamaku di negen orang.
Tiga bulan pertama aku ikuti kursus bahasa Inggris di Lab Bahasa UNSW, dan dua semester aku ikuti mata kuliah computing science. Selanjutnya aku selesaikan program kuliah tingkat Master-ku dalam satu-setengah tahun. Awal 1982 aku resmi memegang gelar akademik Master of Surveying Science (M.Surv.Sc.).
Melintasi Garis Khatulistiwa ke Belahan Bumi Utara
Membuka catatan kecil-ku, tersimpulkan sampai dengan saat itu aku belum pernah melewati equator. Artinya, aku baru hidup di belahan bumi selatan saja. Kapan aku melewati garis khatulistiwa dan menginjakan kaki di Lintang Utara? Ini harus aku pecahkan. Pucuk dicinta, ulam tiba, aku ditugasi Kepala BAKOSURTANAL ke Italia dipertengahan tahun 1984 mengikutit program the International Summer School on Geodetic Network Adjustment and Optimization yang diselenggarakan oleh the International Association of Geodesy (IAG), tepatnya di kota tua Erice di pulau Sisilia, Italia. Dari novel dan cerita film yang aku baca dan lihat, Sisilia adalah gudang bandit “Mafia” Italia. Negeri di lintang utara dan di Eropa (Barat). Ini dia yang kucan. Dan topiknya Adjustment…, itu sih topik yang aku sukai. Jadi apalagi?, walau Italia beken dengan geng Mafia tapi aku nggak miris atau keder, tapi senang dan berbunga-bunga.
Di antara catatan dari Italia yang aku torehkan di buku kecilku: Aku berhasil masuk belahan bumi Utara, namun harus bayar cukup mahal juga. Mafioso di Roma mendongku dan uangku sebanyak 500 USD plus puluhan-ribu Lira dirampas dari saku dan dompetku, saat transit menuju Sisilia. Seumur hidupku baru kali ini aku tak berkutik kena todong. Aku putuskan tidak melawan. Biar aja mereka ambil uangku di dompet dan saku. Toh, aku masih ada uang karena aku selalu ikuti nasehat “orang kampung”: “simpanlah sebagian besar uangmu dikaos kaki bila kamu bepergian ke kota”, dan Itulah yang menyelamatkan perjalananku di Italia.
Meraih Impian Waktu SD
Aku masuk Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geodesi pada tahun 1971 boleh dikatakan sebagai “pelarian” karena enggan masuk Kedokteran seperti harapan orang tua. Sebagai mahasiswa di Universitas ternama di negeri ini, Universitas Gajah Mada (UGM), tentu saja aku bangga. Mimpiku ketika masih di Sekolah Dasar adalah pengen jadi Insinyur dan kemudian Jadi Doktor (bukan dokter). April 1978, setelah melewati perjuangan dan suka-duka serta dinamika perkuliahan, praktikum, kerja-praktek, ujian (termasuk uji mental), dan pendadaran yang panjang, akhirnya aku diwisuda juga menjadi Insinyur Teknik Geodesi. Tercatat sebagai lulusan pertama dari angkatan 1971.
Menjelang akhir tahun 1984 aku disodori formulir pendaftaran Overseas Fellowship Program (OFP) dari Menteri Riset dan Teknologi (Menristek). Setelah melewati berbagai test dan seleksi, aku lolos untuk mengikuti program Doktor dan pertengahan tahun 1965, aku berangkat ke Newcastle, Inggris. Professorku terkesan dengan kemampuan computer programming-ku, dan karena aku rajin proyek juga punya pengalaman dalam pekerjaan survey, aku diminta untuk menjadi assistennya dalam matakuliah Geodetic Surveying dan Geodetic Computation. Lumayan…aku dapat tambahan honor £££!
Dengan berbekal Master dari Australia dan berbagai pengalaman interaksi sosial di negeri sendiri dan di negeri orang sebelumnya, tidak terlalu sulit bagiku untuk hidup dan beradaptasi di Inggris. Program risetku pun lancar, dan mimpi anak SD dulu pun tercapai ketika aku dinyatakan lulus dalam sidang disertasi tanggal 22 Desember 1988 di University of Newcastle upon Tyne, Inggris. Bonusnya, aku dikaruniai Allah SWT anak nomor empat yang lahir di Newcastle.
Ilmu dan Amal Menjadi Bekal
Setiap Muslin pasti mendapat ajaran: “Tiga hal yang akan menolong-mu terbebas dan api neraka nanti: (1) amal perbuatan (iman-Islam) baik-mu di dunia. (2) do’a anak-anak) mu yang sholeh, dan (3) ilmu yang berguna yang engkau tinggalkan”. Sungguh Allah Mana Besar
Setarnat S3 di Inggris, Prof. Jacub Rais menugaskanku untuk menangani Dinas Geodesi (1989-1994) dan sebuah proyek geodinamik di sepanjang sesar Sumatera, bekerja sama dengan UNAVCO dan University of California at San Diego, USA. Tahun 1995 aku dila untuk menangani proyek geodinamika Asia Tenggara kerjasama dengan negara-ne ASEAN dan European Commission (EC), disebut EC-ASEAN Geodyssea Sebelum ital tahun 1993 selama 6 bulan aku menjalani Posdoctoral Study on Geodynamics di Inatm Angewandte Geodasie (IIAG) di Frankfurt, Jerman. Ini lah awal “petualanganku memaav kerak bumi dalam kerangka program dunia: “Global Disaster Prevention Programes” yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Program ini melibatkan periset lintas negara, dan memungkinkanku memanca-negara dan melanglang buana ke manca-negara: Perancis, Jerman, Canada, Amerika Serikat, China, Jepang, French Noumea, Tahiti, Kolombia, serta negara tetangga Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Di negeri sendiri, baru tahun 1989 aku menorehkan sejarah melewati equator. Awal tahun 1989, start dari Lampung (gunung Dempo) aku melakukan survei rekonesen untuk proyek geodesi-geodinamika GPS-GPS di sepanjang sesar Sumatera. Catatan: nama GPS-GPS adalah singkatan dari “Geodynamics Project in Sumatra using Global Positioning System”, dan aku lah inventor nama GPS-GPS tersebut. Mulai dari Lampung ke Utara menyusuri Bukit Barisan, singgah di kota-kota Sumatera menembus ke Lintang Utara negeri ini. Tahun 1992 garis khatulistiwa di Kalimantan aku tembus dalam perjalanan Pontianak ke Singkawang hingga Sanggau. Tahun 1993 melewati equator bumi Sulawesi.
Dari Batas-batas Lempeng Tektonik ke Batas-batas Kekuasaan dan Yurisdiksi
Pelajaran pertama ilmu leaderships aku terima tahun 1972, tersimpulkan bahwa: Jangan kau lihat berapa luas “wilayah teritori” dan tingginya tingkat kekuasaan yang engkau dapat, yang penting: Kibarkan bendera dari “wilayah teritori”-mu ke sekeliling, dan tebarkan “warna perubahan…dan orang akan mengenalmu. Ini aku peroleh sewaktu mengikuti Leaderships Basic Training (BATRA) dari sebuah organisasi kemahasiswaan Islam ‘terbesar di extra-kampus UGM Yogyakarta tahun 1972. Itu bukan “motto”, itu telah jadi fakta sejarah. Kata-kata itu pulalah yang selalu meng-inspirasi-ku ketika ditugaskan/ditempatkan apa saja dan di mana saja. Apa lah artinya jabatan pimpinan yang tinggi, kalau kita tidak dapat “mengibarkan bendera dan memberikan warna perubahan” kepada sekitar kita. Itu lah bukti eksistensi kepemimpinan kita, sehingga orang kenal akan karyamu. Apa lah artinya diberi “wilayah teritori” kekuasaan yang luas dan tinggi, apabila kita tidak bisa mengelola “wilayah teritori” dan memberi warna perubahan sebagai adanya kekuasaan yang dimiliki.
Pada tahun 2001 di BAKOSURTANAL dibentuklah “Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW), dan aku ditugaskan untuk menakhodai unit organisasi ini. Entah apa dasar pemikiran Kepala BAKOSURTANAL menugaskan ku memimpin PPBW ini. Tapi ini lah tantangan bagiku, dan aku terima tugas itu sebagai amanah dengan senang hati. Dan…”sekali layar terkembang, pantang aku surut melaut”. Inilah awal “petualangan” surveyorku yang baru. Visi-ku secara populer: “kibarkan bendera dan berikan warna peran surveyor geodesi, bukan sebagai juru-ukur batas, tapi sebagai insinyur dan disainer batas wilayah”.
Dari mana aku harus mulai “petualanganku” dalam “dunia” batas wilayah? “Iqro!”. baca-lah! Itu lah yang menginspirasiku kala mengemban tugas baru, aku harus mulai dari membaca. Dokumen demi dokumen aku cari dan aku baca, buku demi buku tentang boundary making aku pelajari, situs-demi-situs internet aku sambangi. Apa yang kucari? Konsep, pengertian, pemahaman, persoalan, input, proses, output, dan tentu saja termasuk dasar filosofis, landasan teori, landasan hukum, serta berbagai aspek terkait/ikutannya. Apa-bagaimana-mengapa dengan batas negara Indonesia-negara tetangga? Apa-mengapa-bagaimana bangsa/negara lain mengelola masalah batas-batas negaranya? Apa dan bagaimana pendapat para ahli tentang batas wilayah? Demikian pula dengan batas-batas daerah: Ada apa, mengapa dan bagaimana batas-batas antar daerah otonom di Indonesia. Subhanalloh pikirku, ini bukan pekerjaan dan tugas “abal-abal”. Ini terkait masalah teritonal kadaulatan, keadilan, pertahanan, keamanan, yurisdiksi, aset kekayaan negara, kebangsaan, kependudukan, politik luar negeri, politik dan administrasi pemerintahan dalam negen perimbangan keuangan, konstitusi dan hukum, serta jati diri dan harkat-martabat bangsa.
Berikut segmen terakhir dari tulisanku ini merupakan kristalisasi dari sumbangsih seorang surveyor geodesi dalam rangka keutuhan wilayah NKRI.
1. Undang Undang tentang Perairan Indonesia adalah Produk Hukun Nasional Pertama
Awal penugasanku menangani pemetaan batas wilayah tidaklah mudah. Sebagai surveyor yang memiliki latar belakang akademik tentu tidak sembarang menjalankan tugas. Aku tidak suka BAU alias bussiness as usual. Visi-ku dalam tugas ini adalah “Surveyor geodes bukan hanya juru ukur batas, tetapi harus menjadi boundary engineer and designer, dan berkibar di internasional”. Dengan 85% batas wilayah negara RI adalah lautan, dua-per-tiga wilayah NKRI adalah laut dan sepertiganya adalah daratan. Jadi… masalah perairan adalah determinan seluruh wilayah negara. la lah pemersatu Nusantar dan roh Pasal 25A UUD-1945 Maka selayaknya para pendiri Bangsa Indonesia berfikir ke-Nusantaraan, Undang Undang Nomor 4/Prp. 1960 (UU No.4/Prp. 1960) ditetapkan untuk mengukuhkan Deklarası Djuanda pada 13-12-57, menggatikan Ordonansi Belanda 1939 tentang Territoriale Zee en Maritime Ordonantie (TZMKO-1939)…dan UU tersebut telah ‘menggegerkan’ dunia!
Di kuliah dulu masalah batas hanya batas tanah, batas persil kepemilikan dan yang terkait dengan hak-hak warga negara atas tanah. Hukum Agraria adalah acuannya. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA; hukum Agraria) aku amini sebagai produk hukum nasional yang pertama di negeri ini. UUPA ini pula yang aku dulu amini sebagai yang produk hukum yang paling erat hubungannya dengan ilmu geodesi ukur tanah dan pemetaan sebagaimana aku tekuni di Teknik Geodesi. Ternyata setelan aku terlibat dalam urusan batas wilayah, aku temukan lain, dan kesimpulanku, …undang undang produk nasional yang pertama adalah UU No. 4/Prp. 1960 tentang Perairan Indonesial Intinya Hukum Laut, dan ternyata hukum inilah yang paling sarat dengan muatan limu Geodesi, Surver dan Pemetaan (baik dalam teori maupun praktek)…melebihi Hukum Agrarial Mau bukti? Datanglah berdiskusi dengan-ku.
Bagaimana saratnya aspek Geodesi, Survei dan Pemetaan dalam Hukum Laut? Buka lah UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 tahun 1985. Telisik saja dan Bab I sampai Bab XIV yang berisi 278 pasal (dan lihat juga Annex II-nya) dari UNCLOS yang berisi 17 Bab dengan 320 pasal dan 8 Annexes. Pasal-pasal dan Annex tersebut telah dielaborasi oleh para ahli dunia dibidang Oseanologi, Hidrografi, dan Geodesi agar interpretas teknisnya mudah dipahami oleh para praktisi Hukum Laut. Elaborasi teknis tersebut tersusun dalam sebuah buku Panduan (Manual) bertajuk “The Technical Aspects of the Law of the Sea” (TALOS) setebal 206 halaman. Fakta ini menunjukkan betapa Hukum Laut sangat sarat dengan kandungan ilmu geodesi, survei dan pemetaan itu wilayah kerja profesi kita. Lebih lanjut, Indonesia adalah sebagai negara pihak terhadap UNCLOS 1982 sejak tahun 1985, jadi tidak ada kata lain bagi kita di Indonesia, khususnya para Surveyor Geodesi dan Pemetaan untuk memahami dan mendalami UNCLOS dengan TALOS-nya. Dengan kondisi tersebut. setayaknya di Indonesia kita memiliki sebuah Forum Pengkajian TALOS, yang wacananya mulai tahun 2007 dengan sebutan Indonesian Forum on the Technical Aspects of the Law of the Sea (IFOTALOS), terakhir aku angkat lagi wacana ini dalam persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan dan Seminar ABLOS (the Advisory Board on the Law of the Sea) tahun 2009 di Bali.
Atas kesimpulan dan wacana di atas itulah beberapa tahun yang lalu aku menyarankan agar materi Hukum Laut diberikan sebagai Mata Kuliah Pokok di Jurusan Teknis Geodesi di Indonesia. Harap diingat: Wilayah perairan negara kita dua kali wilayah daratan, belum lagi ditambah dengan luas ZEE Indonesia sekitar 3 juta Km². Walau kecil ‘wilayah’ profesi kita: “kibarkan, dan warnai lah, negeri ini dengan karya-mu”.
2. Merajut Pagar Batas Negara
Lain batas daerah, lain batas negara. Apabila ditinjau dari sisi volume, jelas permasalahan batas daerah jauh lebih banyak dibandingkan dengan batas negara, tetapi bukan berarti batas negara lebih sederhana permasalahannya dibanding batas daerah. Kenapa?, Dalam konteks batas negara selain masalah-masalah memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu terkait politik dan hubungan luar negeri, serta setiap aspek dan elemennya pun jauh berbeda. Menangani batas negara bagaikan membuat ‘pagar’ batas negara baik secara bersama dengan negara tetangga (bilateral dan/atau trilateral) maupun secara sendiri (unilateral) yang harus merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri elemen politik, hukum dan teknis, sebagai elemen penyelesaian batas negara, yang intense digarap melalui kebijakan “Border Diplomacy” dalam Politik Luar Negeri RI. Lalu apa hubungannya dengan peta, dengan geodesi. dengan profesi kita, surveyor? Dalam border diplomacy sangat jelas peran Surveyor Geodesi sebagai “boundary maker”, baik sebagai designer, engineer, maupun juru-ukur. Semua aku lalui, baik sebagai anggota Tim Perunding Batas-batas Maritim Negara (Aku selalu bertugas sebagai Ketua Technical Working Group yang bertugas merancang, menggambarkan, dan menganalisis berbagai kemungkinan garis batas laut bersama negara tetangga). Ketua Sub-Komisi Teknis Survei dan Demarkasi Batas Darat (bertugas menegaskan garis batas traktat batas darat masa kolonial berdasarkan prinsip hukum internasional “uti posidetis juris”), dan sebagai Anggota Komisi Bersama Perbatasan (Joint Border Commission: JBC) Indonesia dengan negara tetangga, sejak tahun 2002 hingga tulisan ini aku buat.
Lain batas laut, lain pula batas darat. Di dalam batas laut keahlian geodesi, survei dan pemetaan sejalan dengan aspek teknis dari hukum laut. Sedangkan untuk batas darat antar negara kehadiran dari ahli geodesi, survei dan pemetaan dapat dilihat mulai dari prinsip hukum internasional “uti posidetis juris” dan transkripsi legal dalam traktat batas darat yang dibuat di era kolonial. Itu fakta hukumnya. Hingga saat ini penanganan batas darat Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor-Leste belum seluruhnya tuntas. ‘Pagar’nya masih harus dirajut karena masih ada ‘bolong’ di sana-sini. Sebut saja masih adanya “outstanding boundary problems” (OBP) dengan Malaysia, adanya “un-resolve segments” dan “unsurvey segments dengan Timor-Leste, dan adanya “geodetic datum problems” dan densifikasi pilar batas dengan PNG. Walau secara prinsip hukum Internasional telah ada delimitasi batas darat di Kalimantan, Irian, dan Timor menurut traktat batas yang dilakukan oleh Balanda dengan Inggris dan/atau Portugis sekitar 100 tahun yang lalu, namun untuk membumikan hasil delimitasi tersebut tidaklah mudah. Mengapa?
Pertama bentang alam yang dideskripsikan dalam traktat sering dijumpai telah berubah saat ini dibanding ketika traktat tersebut dibuat (100 tahun yang lalu). Kedua, diperlukan surver yang rinci dan teliti untuk menegaskan dimana letak titik-titik garis batas tersebut dimuka bumi, serta memasang tanda-tanda (pilar/patok) batas, menentukan koordinatnya dengan teliti, dan memetakannya secara lengkap sehingga mudah dipahami banyak orang dan dapat direkonstruksi apabila dikemudian hari rusak atau hilang. Inilah proses survei demarkasi. Ketiga, secara teknis definisi garis batas yang mengikuti bentang alam (seperti watershed dan thalweg) menurut traktat kebanyakan tidak jelas lagi di lapangan, belum lagi yang menggunakan angka koordinat geografis.
tetapi tanpa acuan yang jelas secara konsep geodesi. Misalnya batas darat antara Indonesia dengan Papua Nugini: angka koordinat meridian 141° Bujur Timur dimaksud merujuk kepada sistem koordinat apa? Bila atronomis rujukan epoch-nya kapan? Bila meridian peta, peta yang mana? Apabila dikonversi ke sistem koordinat yang operasional sekarang, bagaimana hubungannya? Keempat, masalah persepsi dan interpretasi diantara kedua belah pihak yang sangat mungkin berbeda. Penyelesaian hal ini jelas perlu waktu dan keahlian substansi didukung dengan keahlian berargumen dalam perundingan.
Terkait batas negara darat antara Indonesia dengan Timor-Leste, adalah karya surveyor geodesi yang terlampir pada sebuah Provisional Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor-Leste yang ditanda tangani pada tanggal 8 April 2005 (PA-2005) oleh Menteri Luar Negeri kedua Negara, disaksikan oleh Presiden Indonesia dan Presiden Timor-Leste. Sungguh aku bangga, selaku Ketua Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR) di pihak Indonesia, aku lah yang memparaf dokumen lampiran-lampiran PA yang terdiri dari: satu lembar peta skala 1:75.000, tujuh belas (17) lembar peta skala 1:25.000, dupuluh tujuh (27) peta Ikonos skala 1:10.000, dan daftar koordinat sebanyak 907 titik penentu batas darat dalam sistem datum geodesi WGS-1984. Perlu dicatat, bahwa kiranya PA-2005 tersebut tidak mungkin ditanda-tangani Menlu RI apabila tidak aku paraf lampirannya. “Surveyor work helps politics touching the earth”, itulah kesimpulanku, sekaligus memperkaya pengabdian seorang surveyor geodesi bagi keutuhan wilayah NKRI.
3. Dinamika Perundingan dan Penentuan Batas Maritim
Selama tujuh tahun hingga saat ini, kehadiran surveyor geodesi turut menentukan dalam perundingan batas-batas laut atau batas maritim. Ada beberapa rejim batas laut yang harus difahami dan dikuasai aspek hukum dan aspek teknisnya, yaitu batas laut teritorial, batas ZEE, dan batas Landas Kontinen. Selama ini aku mendapat tugas sebagai Ketua Technical Working Group dalam Tim Perunding Batas-batas Maritim Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri RI. Perundingan yang telah dan sedang ditangani adalah batas laut teritorial dengan Singapura. Hasilnya baru saja disepakati garis di segmen sebelah barat Selat Singapura pada tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh kedua Menteri Luar Negeri, setelah melalui perdebatan dan negosiasi selama kl, empat tahun (dimuali tahun 2005). Kini masih tersisa dua segmen batas di sebelah Timur selat Singapura. Hasil perundingan tersebut kelihatannya hanya sepenggal garis pendek saja, tetapi sangat akan memiliki dampak kepada (i) kepastian hukum, (ii) kejelasan integrasi wilayah negara, (iii) kejelasan bagi operator penegak hukum di lapangan, dan (iv) mendukung terciptanya perdamaian dan stabilitas politik di kawasan. Teknis memang yang kita lakukan, tetapi berdampak luas dan multi disiplin. Kini masih dan sedang berlanjut perundingan batas maritim dengan Malaysia, yaitu: (i) batas-batas laut teritorial di segmen Selat Malaka bagian Selatan, segmen perairan Tanjung Datu, Kalimantan, dan segmen Selat Siboku lepas pantai pulau Sebatik, ditambah segmen baru di sebelah Timur Selat Singapura pasca keputusan ICJ tentang sengketa Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca, (ii) batas ZEE di Selat Malaka, Laut China Selatan dan Laut Sulawesi, dan (iii) batas Landas Kontinen di Laut Sulawesi atau dikenal dengan kawasan Ambalat.
Ada catatan teknis menarik dari hasil perundingan batas laut teritorial antara Indonesia dengan Singapura, yaitu “Geodetic Datum Problem” untuk menyambungkan titik-titik koordinat garis batas hasil perjanjian tahun 1973 (enam titik koordinat) dengan yang baru disepakati tahun 2009 (tiga titik koordinat). Datum geodesi dari keduanya jelas berbeda, yang baru koordinatnya merujuk ke datum global WGS-1984 yang praktis bisa di-fixing di lapangan dengan menggunakan GPS, sedangkan yang lama rujukan datumnya tidak jelas, hanya ada informasi tentang British Admiralty Chart (BAC) sebagai rujukan perjanjian 1973. Peta BAC tersebut dibuat pada tahun 1967 dan datum geodesinya sangat mungkin adalah datum lokal. Maka secara konsep geodesi garis batas pada tahun 1973 tidaklah berada pada satu bidang dengan garis batas yang baru dibuat pada tahun 2009. Apa solusinya? Jelas harus ada, dengan metoda transformasi datum secara numerik-analitis, atau dengan metoda kartometrik digital. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya yang akhirnya bisa disepakati satu metoda yang aku ajukan sebagai metoda kompromistis tanpa meninggalkan konsep geodesi, tetapi dipahami ahli hukum yang biasa memiliki pandangan lain. Konsep yang aku tawarkan adalah: “Define the coordinates precautionaly precise, but adequately right”. Argumenku ini untuk menghindari kesalahan prinsip yang sering terjadi dan dilakukan bahkan oleh para surveyor sekalipun dikarenakan kurang memahami konsep geodesi. Yaitu: “You can define coordinates very precisely, but absolutely wrong”. Apa jadinya bila itu menyebabkan salah posisi hingga ratusan meter di Selat Singapura yang Sempit? Bentrok senjata antar pasukan patroli laut dapat saja terjadi. Disinilah peran surveyor geodesi dalam mendirikan “good fences for good neighbors”, tidak kah ini secara esensial menyumbang perdamaian kawasan?
Mengawal Revisi PP No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia adalah tugas surveyor geodesi. Di dalam setiap perundingan, salah satu landasan berunding yang penting adalah daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2002. PP ini penting dan strategis artinya dalam merajut ‘pagar’ batas negara, karena PP ini berfungsi sebagai ‘fondasi pagar’ batas negara. Namun ada dua keputusan berdimensi politik dan hukum internasional pada tahun 2002 yang mengharuskan PP tersebut direvisi, yaitu: (1) Kemerdekaan Timor-Leste pada tanggal 20 Mei 2002, dan (2) Keputusan International Court of Justice (ICJ) pada tanggal 16 Desember 2002 tentang status kepemilikan pulau Ligitan dan pulau Sipadan sebagai milik Malaysia. Intensifnya perundingan dengan Malaysia terkait kasus Ambalat sejak tahun 2005 menjadi triger untuk segera merevisi PP No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Demikian pula dengan ditanda tanganinya PA-2005 tentang Batas Darat antara Indonesia dengan Timor-Leste pada tanggal 8 April 2005 menjadi triger untuk segera menyiapkan calon titik-titik dasar di sekitar perairan selat Ombay, selat Wetar Selat Leti, dan Laut Timor. Persiapan revisi diawali dengan melakukan survei dan penentuan posisi calon titik-titik dasar melibatkan BAKOSURTANAL dan Dinas Hido-Oseanografi TNI-AL.
Proses selanjutnya adalah harmonisasi aspek legal dan substansi teknis yang melibatkan lintas instansi, antara lain: Dephuk-HAM, Sekretariat Negara, Deplu, Dephan, Dep K&P, BAKOSURTANAL, Dishidros TNI-AL, dan Kemenko Polhukam. Kesepakatan interdep menugaskan BAKOSURTANAL mengkoordinasikan harmonisasi substansi teknis berkenaan daftar koordinat dan aspek teknis lainnya. Dalam hal ini Kepala BAKOSURTANAL menugaskan Kapus Pemetaan Batas Wilayah sebagai Penanggung jawabnya. Sedangkan untuk harmonisasi aspek hukum koordinasinya dilakukan oleh Dephuk-HAM, cq. Ditjen PP Seluruh hasil harmonisasi dari Dephuk-HAM dan BAKOSURTANAL disampaikan kepada Sekneg untuk finalisäsi naskah PP untuk ditetapkan oleh Presiden. Namun sebelum naskah PP disyahkan oleh Presiden, Mensesneg memintakan konfirmasi/persetujuan atas naskah akhir kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Meriteri Kelautan dan Perikanan, Menko Polhukam, serta Kepala BAKOSURTANAL. Cukup panjang dan memakan waktu memang, tapi itulah prosedur yang harus dilalui untuk lahirnya sebuah PP. Hingga akhirnya pada bulan Juli 2008 ditetapkanlah PP No. 37 tahun 2008 tentang Revisi PP No.38 tahun 2002. Tidak semua isi PP No.38/2002 diubah dengan PP No.37/2008, maka agar tidak salah penggunaan dan dalam rangka pendepositan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) PBB di New York sesuai ketentuan UNCLOS-1982, Deplu dan BAKOSURTANAL menyiapkan sebuah dokumen ‘consolidated table’ dari PP No.38/2002 dan PP No.37/2008 dalarn bahasa Inggris. Pada tanggal 9 Maret 2008 Indonesia resmi mendepositkan Daftar Koordinat Geografis Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia ke Sekjen PBB di New York, dan sekarang masyarakat bisa mengakses daftar koordinat dimaksud di website UN.
Mengawal Submisi ECS Indonesia ke UN-CLCS di New York; Sesuai ketentuan Pasal 76 UNCLOS 1982 negara pantai dari para pihak terhadap UNCLOS dapat mensubmis batas landas kontinennya hingga diluar 200 NM, asalkan memenuhi syarat-syarat tersebut didalam Pasal 76, dengan batas waktu 13 Mei 2009. Untuk maksud tersebut Indonesia, cq. BAKOSURTANAL dengan bekerjasama dengan berbagai instansi telah melakukan kajian sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh UN-CLCS (United Nations Commission on the Limit of Continental Shelf). Indonesia mengindikasikan ada tiga ‘area’ yang akan disubmisi yaitu sebelah barat Sumatera, sebelah Selatan NTB, dan sebelah Utara Papua. Submisi Indonesia akan dilakukan secara parsial, diawali dengan sebelah Barat-Laut Sumatera yang telah dipresentasikan pasa tanggal 24 Maret 2008 di sidang Pleno CLCS di New York, Aku sendiri ikut hadir mengawal paparan Indonesia di CLCS. Ini pengalaman baru/pertama bagi Indonesia, dan baru pula bagiku, dan bagi surveyor geodesi ambil bagian dalam merealisasikan Pasal 76 UNCLOS 1982. “One more step moving forward, viva surveyor!
4. Komunikasi Publik Data Geospasial dan Batas Wilayah
Pada tahun 2003, setahun lebih aku menjabat Ka-Pus PPBW, ada dua keprihatinan yang dirasakan sebagai anak bangsa, yaitu (1) pasca keputusan ICJ tentang sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan, marak pemberitaan di media massa tentang isyu perbatasan disertai dengan simpang siumya pendapat para pejabat (politik dan birokrasi) tentang batas-batas wilayah negara; dan (2) beredarnya berbagai produk peta wilayah Republik Indonesia di pasaran yang diterbitkan oleh berbagai percetakan/penerbit, tanpa kejelasan referensi batas-batas wilayahnya dengan target pasarnya sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SLTA.
Bayangkan, bila sejak dini anak-anak sekolah sudah mendapat konsumsi informasi batas dan wilayah negara yang keliru. Apa jadinya, bila mereka nanti jadi pejabat? Benar kata Jaya Suprana: “ilmu Kelirumologi berkembang subur di Indonesia”. Ini adalah masalah gatra pembangunan pertama yang mendasar: Geografi!, “geography is the destiny!”. Tapi, siapa yang harus bertanggung jawab? Ada sementara pihak yang mengatakan itu tanggung jawab BAKOSURTANAL, benarkah? Nah, daripada aku berkutat dengan berbagai pertanyaan yang belum tentu jawabnya, aku berpikir bahwa aku harus berbuat. Apa, yang mesti aku perbuat? Waktu itu terpikir jawabnya adalah: Komunikasi publik!
Ada dua metoda komunikasi publik yang aku lakukan: pasif dan aktif yang keduanya dilakukan di instansiku. Komunikasi publik yang pasif sifatnya adalah melalui (i) penerbitan Peta NKRI yang dilengkapi dengan deskripsi lengkap tentang batas-batas wilayah dan yurisdiksinya, disebarluaskan ke berbagai instansi pemerintahan, beberapa lembaga pendidikan, kantor perwakilan RI di luar negeri, dan (ii) penerbitan buku tentang perbatasan, “Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia”.
Komunikasi publik yang bersifat aktif dilakukan dengan diseminasi informasi secara naratif langsung kepada audien, melalui berbagai fora pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi, media massa cetak/elektronik, dialog di televisi/radio, internet, termasuk debat publik aku jalani. Sungguh, selama ini para surveyor geodesi kurang menyadari perlunya komunikasi publik sebagai sarana pencerdasan bangsa. Aku berkesimpulan bahwa ketidak/belum berhasilan BAKOSURTANAL (sebagai tempat para ‘elit surveyor’ berada) melahirkan sebuah ‘undang-undang tentang survei dan pemetaan nasional’ atau ‘undang-undang tentang tata informasi geografis nasional yang disingkat ‘TIGNAS’ yang kepanjangannya sekarang menjadi ‘tata informasi geospasial nasional, adalah kurang seriusnya melakukan komunikasi publik. Dari komunikasi publik akan menghasilkan opini, dan opini bisa diarahkan ke komunikasi politik.
Beberapa kali aku jadi nara sumber dan diwawancara media massa cetak dan elektronik. Bukan karena aku ingin terkenal tapi Ini adalah bagian dari ‘pengibaran bendera’ dan upaya mengubah persepsi masyarakat tentang masalah perbatasan yang aku lihat/dengan tidak proporsional, atau malah keliru, serta ingin meluruskan duduk persoalan secara benar. Beberapa contoh yang sering aku luruskan pada proporsi yang sebenarnya adalah: Kasus Sipadan dan Ligilan, Isu Ambalat, Isu Ekspor Pasir dan Reklarnasi Singapura, Kasus Pulau Batek, Kasus Pulau Miangas, Isu Pulau Berhala, dan Isu Pulau Pasir. Semua itu menyangkut batas negara.
5. Daerah Otonom Perlu Tenaga Surveyor
Sejak diundangkannya UU No. 22 tahun 1999, batas daerah menjadi sangat penting. Permasalahan sengketa batas antar Provinsi atau antar Kabupaten yang sebelumnya tidak terlalu dipersoalkan jadi mencuat dengan tensi yang tinggi, ditambah lagi dengan persoalan batas wilayah antar daerah yang baru dimekarkan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999. Bukan hanya batas wilayah di darat, tetapi juga batas di laut. Bukan hanya terkait yurisdiksi dan administrasi wilayah oleh Pernerintah Daerah (Pemda) tetapi juga menyangkut Fiskal Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sungguh, surveyor geodesi kurang menyadari sebelumnya, demikian pula para pengambil kebijakan/keputusan tingkat nasional dan para pembentuk hukum (legislator) di negeri ini dalam melahirkan UU No. 22 tahun 1999 dan berbagai Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom baru (Pemekaran).
Semula bagai kurang disadari bahwa produk hukum tentang pembentukan daerah harus di-back-up oleh keakurasian dan kelengkapan peta wilayah. Senyatanya pembentuk UU No. 22 tahun 1999 dan turunannya tidak memahami peranan dan pentingnya data survei pemetaan pada awalnya. Tidak ada satu pun pakar survei dan pemetaan (Surta) dilibatkan dalam penyusunannya. Sampai akhirnya, melalui berbagai forum aku “bernyanyi” bahwa peta yang baik dan benar harus menjadi rujukan dalam setiap undang-undang tentang pembentukan daerah. Walau kecil unit organisasi yang aku kibarkan, tapi akhirnya mendapat respon positif juga, surveyor geodesi ikut mewarnai revisi UU No. 22 tahun 1999 dengan UU No. 32 tahun 2004, serta juga mewarnai setiap Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom baru sejak pembahasan tahun 2006.
Melalui instansi tempat aku bekerja, BAKOSURTANAL cq. Pusat Pemetaan Batas Wilayah, sebagai salah satu Anggota Pokja II Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) aku berusaha meyakinkan para birokrat pemerintahan, politikus dan Legislator (khususnya di DPR) agar mau mendengarkan penjelasan bahwa peta yang lengkap dan akurat dengan skala memadai harus melengkapi lampiran Undang-undang tentang Pemekaran. Bukti nyata ini dapat dilihat dalam lampiran UU Pemekaran pasca tahun 2006. Tercatat tidak kurang dari 70 UU tentang Pemekaran Daerah (periode 2006-2008) telah terwarnai oleh surveyor geodesi. Demikian pula dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah Otonom oleh PP No. 78 tahun 2007 telah memasukan pentingnya unsur peta (boleh juga disebut unsur data geospasial) dalam peraturan tersebut. Rentang waktu tahun 2004/2005 sampai 2007, sekitar tiga tahun menunjukkan betapa alotnya pembahasan isu pemekaran dan peran data geospasial agar masuk dalam syarat-syarat. Bandingkan dengan revisi PP No. 25 tahun 2000 dengan PP Nomor 55 tahun 2005 yang merupakan “saudara sepupu dari PP No. 78 tahun 2007. Itulah pemikiran dan warna perubahan yang dapat aku sumbangkan untuk negeri ini.
Cukup menarik memang, ketika berbicara tentang perimbangan keuangan (cq. PP No. 25/2000 sebagaimana telah direvisi dengan PP No. 55/2005) nampak bahwa didalam PP ini telah disadari betul pentingnya data geospasial untuk perhitungan perimbangan keuangan. Pengalamanku menunjukkan hanya satu kali aku menjadi nara sumber dan berbicara tentang pentingnya data geospasial untuk perhitungan perimbangan keuangan dan fiskal daerah di forum Focus Group Discission (FGD) antara Pemerintah (cq. Departemen Keuangan) dan DPR pada awal tahun 2006. Dalam hubungan Fiskal Daerah ini, data luas wilayah menjadi parameter utama dimana kunci dan nara sumbernya adalah survey dan pemetaan. Aku pun ikut membidani lahirnya Permendagri tahun 2008 tentang Luas dan Kode Wilayah Pemerintahan Dalam Negeri, Dinamika lain halnya dengan revisi PP No. 129/2000 dengan PP No. 78/2007 yang terkait dengan berbagai UU tentang Pembentukan Daerah Otonom, aku terlibat beberapa kali dalam diskusi dan perdebatan tentang pentingnya peta atau data geospasial, baik di forum koordinasi Pemerintah (dikoordinasi oleh Departemen Dalam Negeri), maupun di forum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR. Semua menjadi tantangan dan kiprah masuknya Surveyor Geodesi sebagai “boundary engineer and boundary designer” di dalam negeri. Tentu saja dengan bersama disiplin ilmu pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, dan hankam. Pencapaian, sejak tahun 2006 hingga saat ini sekitar 70 UU tentang Pembentukan Daerah Otonom telah dilampiri dengan peta yang memadal, tidak seperti sebanyak 148 daerah otonom yang dilahirkan antara tahun 1999 sampai 2005.
Lalu apa yang tersisa dengan batas daerah? Selesaikah persoalannya? Jawabnya BELUM. Hitung saja saat ini total Pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) ada 531, hanya 70 saja yang peta lampirannya jelas. Nah hitunglah sisanya, jadikan PR atau ‘proyek penelitian batas daerah untuk Kampus Teknik Geodesi. Belum lagi aku masih diberi PR oleh Departemen Dalam Negeri untuk melakukan kajian komprehensif “grand design pemekaran daerah otonom (Provinsi, Kabupaten dan Kota) di Indonesia tahun 2025 ditinjau dan aspek teknis geografi, survei dan pemetaan. Semua nanti juga akan berimplikasi kepada kebutuhan daerah akan tenaga geodesi, survey dan pemetaan yang profesional. Perhatikan UU No. 32 tahun 2004, PP No. 38 tahun 2007, dan PP No. 78 tahun 2008, ditambah lagi denag UU No. 43 tahun 2008 dan turunannya. Nah, cukup jelas geodesi telah berkibar dan memberi warna, tinggal kini semua selalu siap untuk mengisinya. Peranan lembaga Perguruan Tinggi dengan Jurusan Teknik Geodesinya jelas dinanti untuk menghasilkan surveyor-surveyor geodesi yang andal turun ke daerah. “Look our region need us!”.
6. Mengawal Lahirnya Undang Undang tentang Wilayah Negara
Semula aku suka bertanya-tanya kenapa wilayah negara tidak tertera di dalam UUD Ri tahun 1945. Namun setelah aku membaca risalah sidang Badan Persiapan Usaha usaha Kemerdekaan Indonesia ketika menyusun draf UUD 1945, baru lah aku temukan jawabnya. Betapa alot perdebatan para tokoh waktu itu. Ada dua kubu ekstrim, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin, yang sulit dipertemukan pendapatnya dalam hal menyangkut wilayah negara. Keputusannya draf pasal tentang wilayah negara di ‘drop’. Akhimya, dalam Amandemen Kedua UUD 1945, masuklah pasal tentang Wilayah Negara dalam Pasal 25E. yangkemudian dalam Amandemen Keempat menjadi Pasal 25A. Pasal ini mengamanatkan bahwa wilayah negara Negara Kesatuan Republik Indonesia berciri Nusantara, yang batas batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang Undang”. Tahun 2004 mulai lah wacana menyiapkan draf undang-undang sebagai penjabaran Pasal 25A UUD 1945 digarap oleh Pemerintah, dengan judul draf: “Undang-undang tentang Batas Wilayah Negara yang kemudian dead-lock. Hingga akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) usul inisiatif pada awal tahun 2007. Judul RUU awalnya sama tentang Batas Wilayah Negara”. Yang lalu aku sarankan agar RUU inisiatif DPR diubah judulnya menjadi: “RUU tentang Wilayah Negara yang ternyata kemudian diterima oleh Baleg DPR. Setelah melewati proses pembahasan yang panjang dan intensif, keputusan akhir dibuat DPR pada Sidang Paripurna tanggal 28 Oktober 2008, dan Undang Undang-nya diundangkan tanggal 14 November 2008, sebagai UU No.43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Rasanya cukup lumayan kontribusi pemikiranku (sebagai seorang surveyor geodesi) dalam undang-undang tersebut, bukan hanya menyangkut judul, tetapi juga terkait pengertian, definisi dan istilah (Bab I Pasal 1), dan isi pasal-pasal lainnya. Dan membuat aku tersanjung dengan diundangkannya UU No.43 tahun 2008 ini pada tanggal 14 November 2008, yaitu tanggal tersebut adalah tepat dengan tanggal hari kelahiranku. Boleh…lah itu disebut sebagai “kado” ulang tahunku.
7. Mengibarkan Center of Boundary Mapping BAKOSURTANAL di Mancanegara
Sejak tahu 2002 aku mencanangkan visi Pusat Pemetaan Batas Wilayah haruslah berkaliber internasional. Bagaimana mencapainya? Banyak cara asal ada niat dan kemauan, Awalnya di tahun 2003 aku adalah orang Indonesia pertama yang mengikuti training tentang batas wilayah di sebuah pusat riset IBRU (International Boundary Research Unit) di Durham University, Inggris. Aku sangat terkesan oleh IBRU dan aku jadikan IBRU untuk ‘bench marking’ walaupun terlalu jauh rasanya. Tapi aku harus ‘bench marking yang menantang. Hingga kini sudah 10 orang di Bakosurtanal telah mendapat training di IBRU. Semua itu investasi untuk ‘berkibarnya Pusat PBW BAKOSURTANAL di tingkat internasional. Hingga kini Pusat PBW telah membawa Indonesia untuk berbicara tentang batas, bukan hanya dalam perundingan bilateral, tetapi berani tampil di forum internasional, diantaranya sebagai pemakalah di: IBRU Conferences di Universitas Durham (2007 dan 2009), ABLOS Conferences di Monaco (2006 dan 2008), Bangkok International Conference on Land and River Boundaries (2006), FIG Symposium di Cairo (2006), dan Indonesia and the Philippines Seminar di Manila (2009). Selain itu aku membawa Pusat PBW untuk aktif mengikuti studi banding dan riset pustaka tentang perbatasan dan batas wilayah ke beberapa negara, seperti ke: Swiss-topo, BEV Austria, BKG-Jerman, Nat’l Library dan ICJ di Denhaag. UKHO di Tauton, Nat’l Library di Lisabon, IGN di Paris, ITLOS di Hamburg, UN Library di New York, University of Melborne, Namria the Philippines, dan Petronas di Kuala Lumpur.
Epilog
Aku berharap tulisan ini dapat merefleksikan salah satu pencapaian dari alumni Teknik Geodesi UGM yang telah berkiprah di instansi Pemerintah selama lebih dari 30 tahun, tapi sejak mahasiswa pun telah berkiprah. Selain berharap dibaca para dosen agar lebih semangat lagi untuk mencetak sarjana geodesi, aku juga berharap tulisan ini dibaca oleh generasi muda geodesi-wan/-wati, para mahasiswa Teknik Geodesi atau para alumni muda Teknik Geodesi. Maksudku tiada lain untuk memberi motivasi dan cakrawala bahwa peran dan tugas profesi geodesi begitu luas dan menantang. Semua tergantung visi kita sebagal surveyor, tergantung persepsi kita tentang pemimpin.
Surveyor adalah permimpin, sarjana/surveyor geodesi adalah “boundary engineer dan “boundary designer”. Yang penting….niat dan “iqro”. Pesanku: “jangan merasa kecil karena wilayah teritori-mu kecil, kibarkan terus benderamu, dan terus… hingga mewarnai sekitar hingga berubah karena kamu ada”.
——————————-
Dr. Sobar Sutisna, alumni Teknik Geodesi UGM angkatan 1971 (nomor alumni: 18). Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
——————————-
Catatan: Tulisan ini dikutip dari buku Refleksi Inspiratif Pemetaan Jejak Perjalanan Alumni Teknik Geodesi UGM pada rangkaian Peringatan Setengah Abad Teknik Geodesi FT UGM, yang diterbitkan pada 28 Mei 2009.
——————————–